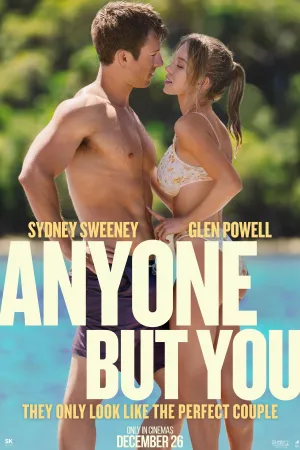Ironi di Balik Kejayaan Spotify: Musisi Dibayar Murah - Musik Dianggap Bak Produk Pabrik

Ilustrasi Musik © Shutterstock.com
Kapanlagi.com - Di balik kejayaan Spotify sebagai raksasa streaming musik dunia, tersimpan sederet ironi yang menghantam langsung para musisi dan pencipta lagu. Meski memudahkan akses publik terhadap jutaan lagu, Spotify justru menempatkan seniman musik dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Salah satu sorotan utama adalah bayaran yang amat minim per pemutaran lagu, serta tekanan sistemik agar para musisi terus memproduksi karya seperti mesin pabrik.
Menurut laporan The Guardian (2021), Spotify membayar rata-rata hanya sekitar USD 0,003 hingga 0,005 per stream setara dengan sekitar Rp50 hingga Rp80 per putaran jika dikonversi ke rupiah.
Advertisement
1. Pendapatan yang Dibagi-Bagi
Dengan nilai serendah itu, seorang musisi baru bisa meraih sekitar USD 1.000 (sekitar Rp15 juta) setelah lagunya diputar lebih dari 250.000 kali. Angka ini tentu jauh dari cukup untuk menopang hidup seniman independen, apalagi jika mereka tidak memiliki kontrak eksklusif atau manajemen yang kuat di belakangnya.
Meski Spotify mengklaim telah membayar lebih dari 70% pendapatannya kepada pemilik hak cipta, angka tersebut tidak serta-merta mengalir langsung ke kantong musisi.
Menurut laporan resmi Spotify dan kajian dari Music Business Worldwide, pendapatan itu harus dibagi-bagi lagi dengan label rekaman, publisher, dan pihak ketiga lainnya. Alhasil, musisi sebagai pencipta konten utama justru sering menjadi pihak yang paling akhir mendapatkan bagian dan dalam jumlah yang terkecil.
(Setelah 8 tahun menikah, Raisa dan Hamish Daud resmi cerai.)
2. Tiada Jeda

Situasi ini membuat banyak musisi mengeluh tentang tekanan untuk terus berkarya secara konsisten tanpa jeda, demi memenuhi tuntutan algoritma Spotify. Model bisnis platform ini cenderung memaksa para kreator untuk terus menghasilkan lagu baru agar tetap relevan dan terbaca sistem.
Seperti yang dikutip dari wawancara Rolling Stone dengan sejumlah musisi independen, mereka merasa seperti robot kreatif yang tidak lagi diberi ruang untuk bereksplorasi secara artistik.
Musik, yang sejatinya lahir dari pengalaman hidup, proses kreatif, dan pencarian makna mendalam, kini diperlakukan layaknya produk pabrik. Keharusan untuk selalu viral, trending, dan tayang di playlist populer membuat musisi kehilangan kebebasan artistik.
3. Dipimpin Bukan Musisi

Penulis lagu sekaligus penyanyi David Byrne, dalam artikelnya di New York Times, menyebut sistem ini sebagai bentuk eksploitasi baru dalam industri hiburan modern yang tak kalah kejam dari era label rekaman konvensional.
Ironi makin terasa ketika mengingat bahwa Spotify dipimpin oleh Daniel Ek, seorang mantan pengembang perangkat lunak yang tidak memiliki latar belakang musik. Ek kerap mengeluarkan pernyataan yang menyinggung cara kerja musisi, termasuk pernyataannya pada tahun 2020.
4. Seperti Barang Pabrik
"Musisi tidak bisa lagi merilis album hanya setiap tiga atau empat tahun." Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai kalangan musisi karena dianggap meremehkan proses kreatif yang tidak bisa dipaksakan seperti produksi barang industri.
Dengan semua fakta ini, muncul desakan dari komunitas musisi global agar sistem pembagian royalti di Spotify diperbaiki dan lebih adil. Kampanye seperti #JusticeAtSpotify yang digagas oleh Union of Musicians and Allied Workers (UMAW) menjadi bukti nyata keresahan yang tak bisa lagi diabaikan.
(Hari patah hati se-Indonesia, Amanda Zahra resmi menikah lagi.)
Berita Foto
(kpl/tdr)
Advertisement